
Nasi goreng spesial, saya pilih fotonya yang nggak terlalu banyak minyaknya  _foto dari hadisida.blogspot.com
_foto dari hadisida.blogspot.com
Negeri yang “Spesial”
Selama 11 tahun lebih bermukim di Bandung dengan gaya hidup ala mahasiswa, saya belajar makna sebuah kata dari sajian kuliner di Kota Kembang ini. Kata tersebut adalah “spesial”. Di warung-warung tenda yang menjadi langganan para mahasiswa (mungkin bukan para mahasiswa bermobil memacetkan Kota Bandung), biasanya Anda akan menemukan menu sebagai berikut:
(1) Nasi goreng ayam
(2) Nasi goreng udang
(3) Nasi goreng cumi
(4) Nasi goreng telur
(5) Nasi goreng seafood
(6) Nasi goreng spesial
“Spesial” pada menu no. (6) berarti, menu (1), (2), (3), (4), dan (5) dicampur menjadi satu. Rasanya bagi saya enak-enak saja. Bandung toh begitu kaya dengan makanan “hybrid”. Pernah menikmati singkong keju? Ice creamgoreng? Bahkan seorang rekan saya pernah menemukan “Es Teh Manis Panas”. Mungkin makanan di Bandung disesuaikan dengan penduduknya yang kosmopolitan. Sebagai catatan, semakin sering saya mendengar logat Makassar atau wilayah-wilayah Timur Indonesia di jalan-jalan kota ini.
Mungkin aneka rasa dan bahan ketika digabungkan bisa menghasilkan rasa baru yang fantastis. Sayangnya, tidak semua hal demikian adanya. Dalam sebuah diskusi politik di UNPAD Ahad (18/03) lalu, ada pernyataan yang sebenarnya tidak baru tapi tetap menggelisahkan. “Sistem kita fragile, terbangun dari berbagai entitas. Pada dasarnya orang Indonesia itu menganut kolektivitas, (tapi?) mencomot sistem dari sana-sini dan menggabung-gabungkannya,” kata Anis Matta, Sekjen PKS.

Diskusi Politik di UNPAD, kerjasama HU Republika, Kemendagri RI, Pusat Studi Kenegaraan Unpad, dan YPM Salman ITB_dok. Republika
Beliau mencontohkan, di masa Orde Lama, UUD ’45 sebenarnya semangatnya cenderung ke arah sosialisme. Tapi entah bagaimana, kebijakan kabinetnya (mungkin maksudnya pada masa Demokrasi Liberal—pen.) justru liberalistik. Sampai sekarang pun, comot mencomot dalam membangun sistem masih terjadi dalam ranah politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, dll. Indikasinya adalah kebijakan-kebijakan dalam bidang-bidang tersebut yang berganti-ganti dan atau tidak jelas arahnya.
Terlepas dari masalah comot-mencomot itu, orang Indonesia sejak dulu mungkin memang senang dengan kondisi “gado-gado”. Bangsa kita dikenal sebagai bangsa yang majemuk. Kemajemukan ini sering digembar-gemborkan sebagai sebuah kekayaan. Dari satu sisi memang itu benar. Tapi pada sisi lain, kemajemukan itu juga sebuah masalah. Katanya, orang Indonesia menghargai perbedaan, tepo seliro.
Mungkin memang begitu di era Orde Baru. Namun, nyatanya, begitu (Alm.) Soeharto lengser, tahun 1999 terjadi kerusuhan Ambon. Ini adalah kerusuhan bernuansa SARA pertama pasca reformasi, yang terus diikuti konflik-konflik SARA berikutnya: Sampit, Poso, Ahmadiyah, dll. Sangat mungkin pula, kemajemukan tersebut turut menyumbang pada kebingungan kita membangun sistem bagi bangsa ini.
Bukankah kita punya Pancasila? Bukankah jelas-jelas di kaki Garuda tercengkeram semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”? Sayangnya, Pancasila yang diciptakan Bung Karno untuk menjadi dasar negara, sampai kini belum berhasil menggenggam harapan ke-bhineka-an tersebut. Lagi-lagi Anis berpendapat, “Ini karena Pancasila adalah konsensus, bukan ideologi.” Pancasila sebenarnya kata Anis, adalah konsensus dari ideologi agama, humanisme, demokrasi dan sosialisme. Karena ia bukan ideologi, maka menurut Anis, “Orang akan sulit sekali menurunkan Pancasila ke dalam sebuah sistem.”
Budaya: Struktur yang Berproses dalam Interaksi
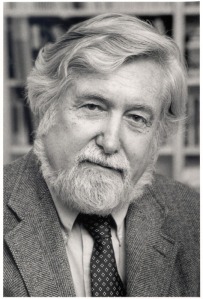
Clifford Geertz, mudah-mudahan Geertz yang ini dan semoga saya tidak salah kutip  _foto dari nosex.tumblr.com
_foto dari nosex.tumblr.com
Sistem, ideologi, agama (sebagai lembaga, bukan wahyu-Nya), klasifikasi ras dan golongan, adalah contoh-contoh struktur, sisi artifak budaya. Budaya punya sisi lain, yaitu proses pemaknaan yang menghasilkan struktur-struktur tersebut. Proses tersebut berjalan lewat interaksi-interaksi antar manusia, yang mau tidak mau harus berlangsung dalam wadah struktur-struktur yang sudah ada sebelumnya. Jadi memang tepat kiranya perkataan Geertz bahwa “Manusia adalah binatang yang tergantung dalam jaring-jaring pengertian yang dipintalnya sendiri.” Struktur dan proses adalah dua sisi budaya yang terus menerus saling mempengaruhi.
Jadi, persoalan kemajemukan di Indonesia dapat dipandang sebagai fenomena budaya, baik pada sisi struktur maupun proses. Telah disebutkan di atas bahwa proses pemaknaan yang menghasilkan struktur-struktur budaya lahir dari interaksi antar manusia. Budaya lahir dari pemaknaan bersama, bukan pemaknaan masing-masing pribadi. Ketika kita bicara “budaya nasional” atau “karakter bangsa”, maka kedua hal tersebut hadir sebagai hasil tukar menukar, negosiasi dan dialog atas pemaknaan “budaya” dan “karakter” masing-masing pribadi.
Dengan demikian, selalu menarik untuk bicara mengenai budaya atau karakter manusia-manusia Indonesia. Budaya, karakter, sifat, atau apapun itu yang melekat dalam kesadaran dan ketidaksadaran manusia-manusia Indonesia, adalah modal dasar yang berkontribusi dalam membentuk sistem, ideologi, agama dan artifak-artifak budaya Indonesia yang majemuk. Kembali saya tekankan, majemuk dengan segala kekayaan dan permasalahannya.
Tentu saja dengan mengingat kembali kutipan Geertz di atas, modal dasar tersebut tercipta dalam struktur-struktur yang sudah ada sebelumnya. Namun toh manusia juga yang mencipta struktur-struktur itu. Karena manusia yang menciptakannya, maka ia pula yang dapat mengubahnya. Ketika wadah ideologi, sistem, agama, dan klasifikasi yang dibuatnya sendiri mulai terasa tak nyaman, manusia selalu berusaha mengubahnya. Sejauh mana dan seperti apa hasil usaha itu nantinya, akan ditentukan lagi lewat proses interaksi dengan manusia-manusia lainnya.
Tidak dapat dipungkiri memang, bahwa proses interaksi tersebut bukan hanya dipengaruhi oleh pemaknaan pribadi masing-masing manusia Indonesia. Faktor lingkungan non manusia turut berpengaruh. Sering kita dengar dan lihat misalnya, bahwa bentang alam yang keras juga menghasilkan manusia berwatak keras. Disamping itu, lebih-lebih kini dalam era globalisasi dan konvergensi media, manusia Indonesia kerap kali pula berinteraksi dengan manusia-manusia dari aneka bangsa dan budaya.
Terlepas dari pengaruh-pengaruh non manusia tersebut, peran manusia dalam mencipta dan mengubah budaya tetaplah sentral. Seandainya manusia bukan aktor utama dalam budaya, tentu struktur-struktur yang ada tidak akan digunakan untuk mengarahkan manusia, “mengisi” manusia dengan pemaknaan-pemaknaan pribadi yang akan mempertahankan struktur-struktur tersebut. Seandainya manusia hanya robot atau bahkan sekrup kecil dalam struktur besar budaya, niscaya tidak perlu ada proses sosialisasi, pendidikan dan penanaman nilai dan norma ke dalam dirinya.
Pendidikan: Jalan Kebudayaan
Sebuah artikel opini yang menarik di Harian Kompaspada Sabtu (07/04), mengupas hal yang baru saja disinggung di atas. Muhammad Abduhzen, Direktur Eksekutif Institut for Education Reform (IER) Universitas Paramadina Jakarta, menulis tentang “pendidikan sebagai jalan kebudayaan”. Mengutip Ketua Litbang PB PGRI ini, “Melalui pendidikan, seseorang mengalami proses pembudayaan dan lewat pendidikan pula sebuah bangsa mewujudkan kebudayaan yang diinginkannya.” Karena itu, yang bersangkutan mengapresiasi dilekatkannya kembali istilah “kebudayaan” pada Kementerian “Pendidikan & Kebudayaan”.
Namun, persoalan terbesarnya kemudian adalah apa yang perlu dididikkan dan ditanamkan ke dalam diri manusia-manusia Indonesia ini? Apakah kita akan menanamkan nilai-nilai yang lama atau menambahkan yang baru? Mana diantara yang lama yang harus dipertahankan? Mana diantara yang baru yang harus diserap? Atau mungkin lebih jauh sebelumnya, sudahkah kita identifikasi secara sadar apa-apa saja nilai-nilai kita yang lama dan mana-mana saja nilai-nilai baru yang perlahan-lahan meresap ke bawah kulit kita?
Ketika kita telah menjawab (setidaknya untuk sementara, seberapa lama pun sementara itu) pertanyaan-pertanyaan di atas, pertanyaan-pertanyaan baru akan datang menghampiri. Bagaimana kita mendidikkan dan menanamkan nilai-nilai yang kita pilih tersebut? Apa wujud implementasi atau indikator tertanamnya nilai-nilai tersebut? Apakah nilai-nilai tersebut akan seragam pemaknaan sampai implementasinya dari ujung Sabang hingga Merauke (sangat mungkin tidak)? Ketika terjadi interaksi antar manusia-manusia Indonesia yang berbeda-beda itu, seperti apa kiranya hasil negosiasi nilai yang terjadi? Begitu pula, ketika interaksi terjadi dengan manusia-manusia bangsa lain, apakah hasil nilai yang disepakati dapat kita ramalkan?
Mungkin ini memang masalah klise, sebagaimana persoalan yang diutarakan Anis Matta di atas. Tapi jelas, ini persoalan yang belum selesai! Abduhzen dalam artikelnya di atas juga mengakui bahwa “Konsep kebudayaan nasional belum begitu terang…”. Dalam kekaburan definisi tersebut, Beliau hanya menyarankan langkah-langkah awal agar pendidikan betul-betul menempuh jalan kebudayaan.
Langkah awal tersebut pertama-tama adalah pemfungsian sistem pendidikan nasional sebagai “upaya penyadaran tentang status manusia: makhluk berkebudayaan.” Maknanya, “para pelajar harus disadarkan bahwa menjadi manusia artinya beramal, yaitu berkarya untuk kemaslahatan bersama.” Langkah kedua adalah pendidikan harus menumbuhkan identitas nasional: “jawaban atas pertanyaan tentang siapa kita sebagai orang dan bangsa Indonesia…”.
Siapa Kita? Setumpuk Pertanyaan
(Alm.) Mochtar Lubis dahulu pernah menyampaikan sebuah ceramah tentang siapa itu orang Indonesia. Ceramah yang disampaikan di
Institut Kesenian Jakarta pada 6 April 1977 tersebut, oleh Yayasan Obor Indonesia kemudian dibukukan dengan judul “Manusia Indonesia: Sebuah Pertanggungan Jawab.” Di dalamnya, Mochtar menyebutkan enam ciri utama manusia Indonesia. Hampir semuanya jelek. Keenam ciri tersebut adalah: (1) munafik atau hipokrit; (2) enggan bertanggung jawab atas perbuatannya; (3) feodal; (4) percaya takhayul; (5) berjiwa artistik; (6) lemah watak atau karakternya, kurang mampu mempertahankan keyakinannya.
Namun disamping itu, Mochtar juga mengakui bahwa manusia Indonesia punya sifat-sifat yang baik. Misalnya, suka tolong menolong, kuat ikatan kekeluargaannya, berhati lembut, penyabar, suka damai, punya rasa humor, dapat tertawa dalam penderitaan, otaknya encer: cepat belajar dan mudah dilatih keterampilan.
Meskipun ada ciri-ciri positif yang disebut, karena yang lebih disorot dalam buku ini adalah ciri-ciri yang terkesan negatif, tak urung ulasan Mochtar dikritik banyak pakar. Namun, Mochtar menerima dan memuat semua kritik tersebut dalam bukunya, berikut tanggapannya pribadi. Untuk langkahnya itu, saya tak ragu menambahkan satu ciri pada manusia Indonesia bernama Mochtar Lubis, yaitu demokratis: mampu menghargai perbedaan pendapat.
Ciri lain manusia (sekaligus masyarakat) Indonesia saya temukan dalam Kuliah Umum Studia Humanika bertema “Kelisanan dan Literasi”. Inti kuliah yang berlangsung di Salman pada bulan Februari-Maret 2011 itu, adalah bahwa masyarakat/manusia Indonesia pada dasarnya masih hidup dalam kelisanan. Atau paling tidak—mengutip istilah S. Kunto Wibowo, M.Comm (dosen dan peneliti Fikom Unpad)—masyarakat Indonesia masih membawa residu kelisanan yang besar. Selain suka mengobrol, ciri-ciri utama manusia/masyarakat lisan adalah keguyuban/kolektivitas yang kuat, dan sikap yang lebih mengutamakan intuisi dibandingkan rasio.
Kentalnya kolektivitas atau keguyuban manusia Indonesia lagi-lagi juga bukan wacana baru. Yang menjadi pertanyaan baru bagi saya adalah, seberapa jauh kolektivitas tersebut bermanfaat atau justru menghambat bagi bangsa Indonesia? Awalnya, saya memahami oposisi kolektivitas-individualitas sebagai berdiri sejajar dengan oposisi intuisi-rasio dan orality-literacy. Lebih jauh lagi, karena individualitas, rasionalitas dan literasi adalah ciri-ciri masyarakat di negara maju, saya menyimpulkan bahwa kolektivitas adalah satu ciri keterbelakangan yang harus ditinggalkan, atau setidaknya dikurangi.
Akan tetapi, ketika mengikuti kuliah Komunikasi dalam Konteks Organisasi, saya mendapat sudut pandang yang menarik dari dosen saya, Prof. Yosi Adiwisastra. Beliau berujar bahwa birokrasi di mana-mana mengalami kegagalan, kecuali di Jepang. Menurut Beliau, Jepang berhasil karena masyarakatnya memiliki budaya atau etos bushido. Bushido kurang lebih disamakannya dengan “kolektivitas”, kesediaan untuk berkorban bagi kepentingan orang banyak. Dengan etos tersebut, para birokrat Jepang benar-benar menjalankan fungsinya sebagai pelayan, bukan orang yang dilayani.
Pembacaan yang simpatik atas kolektivitas, juga disuarakan dalam diskusi politik yang saya kutip pada awal tulisan ini. Arif Wibowo (Ketua Pansus RUU Pemilu dari DPP PDI-P) misalnya, mendorong UU Pemilu kembali ke sistem proporsional tertutup, dengan alasan sistem tersebut lebih sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia yang kolektif. Rata-rata para narasumber hari itu, (kira-kira) menafsirkan kolektivitas sebagai kesediaan untuk “mengutamakan kepentingan orang banyak di atas kepentingan pribadi”.
Pembacaan atas suatu fenomena jelas bisa berbeda, bergantung pada latar pembaca dan sudut pandang masing-masing. Pembacaan-pembacaan yang berbeda tersebut tentunya bukan untuk diletakkan saling berseberangan, melainkan untuk saling melengkapi pandangan. Kajian tentang nilai-nilai, atau lebih jauh lagi karakter, yang harus dididikkan ke dalam diri manusia-manusia Indonesia, akan semakin kaya dan lengkap jika mampu menghadirkan berbagai sudut pandang.
Kolektivitas hanyalah salah satu ciri manusia Indonesia. Masih banyak ciri lain yang perlu diidentifikasi. Sebagai langkah awal kajian tersebut, mungkin kita dapat kembali meninjau karya (Alm.) Mochtar Lubis. Seberapa jauh ciri-ciri negatif dan positif yang dikemukakannya benar-benar hadir dalam diri manusia Indonesia? Adakah ciri-ciri lain yang mungkin luput dari pengamatannya? Apakah ciri-ciri tersebut sepenuhnya negatif atau sepenuhnya positif? Atau dalam redaksi lain: apakah ciri-ciri manusia Indonesia sepenuhnya dapat mendukung kelangsungan dan kemajuan bangsa Indonesia sebagai entitas, atau tidak?
Memahami Diri: Belajar dari Jatuh Bangunnya IBM
Keberhasilan mengenali karakter diri adalah suatu karunia yang luar biasa. Salah satu entitas yang sukses menemukan dan memahami dirinya adalah IBM (International Business Machine). Karena itu, sebagai penutup tulisan ini, saya ingin mengutip sekelumit kisah perusahaan yang dijuluki “The Big Blue” itu. IBM dikenal sebagai perusahaan komputer dan integrator sistem terbesar di dunia. Jumlah pegawainya mencapai 388 ribu orang di seluruh dunia. Perusahaan ini memiliki delapan laboratorium riset di seluruh dunia, berikut ilmuwan, insinyur, konsultan dan tenaga penjualan di 170 negara. Para pegawainya telah meraih 5 hadiah Nobel, 4 penghargaan Turing, 5 Medali Teknologi Nasional, dan 5 Medali Sains Nasional.
IBM berasal dari mergerempat perusahaan pada 1911. Salah satunya adalah Tabulating Machine Company (TMC) yang sukses memenangkan tender dan menjalankan proyek sensus nasional AS pada tahun 1900. Karena TMC menonjol, Thomas J. Watson, Sr., yang menjadi CEO pertama IBM (waktu itu masih bernama CTR, Computing Tabulating Recording) memutuskan untuk memusatkan bisnisnya pada penyediaan mesin pesanan tabulasi berskala besar. Pasarnya adalah instansi-instasi pemerintah baik sipil maupun militer, serta perusahaan-perusahaan swasta besar. Pilihan ini kemudian menjadi ciri khas IBM sebagai penyedia solusi komputasi yang integratif dan spesifik bagi kebutuhan pelanggan-pelanggannya yang berbeda-beda.
Waktu terus berjalan. IBM menjadi leader dalam industri komputer dunia. Komputer-komputer mainframe-nya laris di seluruh dunia. Berbagai inovasinya menyebar ke berbagai sektor, bukan lagi sebatas wilayah birokrasi dan industri. Dua diantaranya yang paling akrab kita gunakan sekarang adalah mesin ATM (cikal bakalnya adalah IBM 3614 Consumer Transaction Facility), dan barcode berikut mesin pemindainya (IBM 3360 dengan sistem barcodeUPC). Jangan lupa bahwa Benoit Mandelbrot, matematikawan yang menemukan konsep geometri fraktal, adalah seorang peneliti IBM.
IBM berjasa dalam membuka jalan bagi kelahiran industri software dan industri layanan jasa komputer (seperti pelatihan dan instalasi peralatan). Pada gilirannya, IBM juga membidani kelahiran PC (Personal Computer). Kemunculan PC dan kemudian teknologi client/server mengubah peta industri komputer. IBM pun tertarik untuk mengikuti gelombang perubahan tersebut.
Namun IBM segera kehilangan dominasi dalam pasar hardware dan softwarePC. Hal ini diakibatkan keputusannya melakukan outsourcing komponen PC ke perusahaan luar seperti Microsoft dan Intel. Sebelumnya, IBM bergantung pada strategi vertikal terintegrasi dengan membangun sebagian besar komponen kunci sistemnya sendiri termasuk prosesor, sistem operasi, periferal,database dsb. Namun untuk mempercepat pemasaran PC-nya, IBM memutuskan meng-outsource prosesor kepada Intel dan sistem operasi kepada Microsoft. Ironisnya, keputusan IBM yang menyerahkan sumber monopolinya kepada Microsoft dan Intel, memuluskan jalan bagi bangkitnya industri PC dan penciptaan pasar bernilai ratusan milyar dolar di luar IBM.
PC membuat komputer berada langsung di tangan jutaan orang penggunanya. Ini diikuti dengan revolusiclient/server yang menghubungkan semua PC (client) dengan komputer-komputer besar yang bekerja di latar belakang sistem (serveryang menyajikan data serta software kepadaclient). Kedua revolusi ini mengubah cara para pelanggan memandang, menggunakan dan membeli teknologi. Keputusan pembelian komputer kini berada di tanagn individual dan departemen-departemen, bukan bagian komputer yang selama ini menjadi pelanggan setia IBM. Kepingan-kepingan teknologi lebih diutamakan daripada solusi integral yang selama ini dijual IBM.
Fokus pemakai telah bergeser pada desktop dan produktivitas personal, bukannya aplikasi bisnis yang dapat dipakai seluruh perusahaan. Sebagai akibatnya, pendapatan IBM yang semula mencapai US$ 5 milyar sejak awal 80-an, merosot menjadi US$ 3 milyar pada tahun 1989. Kenaikan sesaat pendapatan pada 1990 ternyata hanya ilusi di saat pengeluaran perusahaan terus bergeser dari mainframe berkeuntungan tinggi menjadi sistem berbasis mikroprosesor berkeuntungan rendah. Perusahaan terus mengalami penurunan skala bisnis.
John Akers, CEO IBM saat itu, melihat bahwa kompetisi dan inovasi dalam industri komputer kala itu berjalan dalam lini produksi yang tersegmentasi, bukannya terintegrasi secara vertikal. Masing-masing lini memiliki pemain dominannya masing-masing, seperti Novell dalam jaringan, HP dalam printer, Seagate dalam harddisk dan Oracle dalam layanan database.
Karena itu, manajemen IBM dengan dukungan Dewan Direksi memutuskan memecah IBM menjadi unit-unit bisnis yang semakin otonom. Tujuannya agar dapat berkompetisi lebih lincah dengan para kompetitornya, yang lebih fokus dan menggunakan biaya rendah. IBM juga menjual bisnisnya yang dianggap bukan lagi inti. Ia menjual bisnis mesin tik, keyboard, dan printer kepada perusahaan investasi Clayton, Dubilier & Rice Inc. yang menjadi perusahaan independen bernama Lexmark Inc.
Keputusan Akers ternyata kemudian terbukti keliru besar. Pada 19 Januari 1993, IBM mengumumkan kerugian US$ 10 milyar, kerugian paling besar yang pernah dibukukan satu perusahaan selama sejarah AS. Tiga dekade kegemilangan IBM selama masa Watson Jr. selesai sudah. Ratusan ribu karyawan IBM di-PHK termasuk diantaranya John Akers, sang CEO sendiri.
Beruntunglah IBM, ada orang luar yang bisa melihat potensi di dalam IBM. Pada bulan April 1993, IBM menyewa Louis V. Gerstner, Jr. sebagai CEO barunya. Inilah untuk pertama kalinya sejak 1914, IBM merekrut CEO dari luar timnya sendiri. Gerstner sebelumnya adalah ketua dan CEO RJR Nabisco selama empat tahun, dan selama 11 tahun sebelumnya menjadi eksekutif puncak di American Express. Ia membawa kepekaan akan konsumen dan kepakaran berpikir strategis yang dilatihnya bertahun-tahun sebagai konsultan manajemen di McKinsey & Co.
Gerstner membalik keputusan Akers yang mencoba memecah IBM menjadi unit-unit kecil. Alih-alih, Gestner melihat kekuatan IBM justru terletak pada solusi integralnya bagi pelanggan—seseorang yang bisa menyediakan lebih dari kepingan-kepingan teknologi atau komponen. Memecah perusahaan akan menghancurkan kekuatan unik IBM tersebut.
IBM pun kembali mendulang untung, dengan meraih keuntungan sebesar US$ 3 Milyar pada tahun 1994. Perusahaan tersebut mengambil kembali inisiatif bisnis di atas landasan keputusan untuk menjaga perusahaan tetap utuh. IBM menciptakan bisnis layanan global yang dengan cepat muncul sebagai integrator teknologi terdepan. Gerstner sendiri pensiun pada akhir 2002 dan digantikan oleh seorang pekerja IBM senior Samuel J. Palmisano, CEO sampai saat ini.
*******
Terus terang saya sangat terinspirasi dengan kisah IBM ini. Mungkin kisah ini pula yang mendorong saya mengusulkan adanya kajian tentang identifikasi karakter manusia Indonesia, yang dilanjutkan dengan kajian mengenai bagaimana mendidikkan karakter tersebut. Sudah saatnya Indonesia istirahat sejenak dari outward looking dan mulai melakukan inward looking. Bismillah… [salim]





Tidak ada komentar:
Posting Komentar